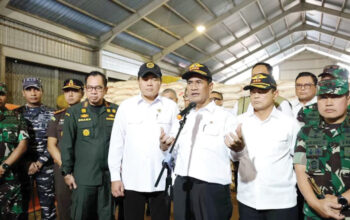OLEH :Roni Efendi (Mahasiwa Doktor Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Unand/ Dosen Hukum Pidana UIN Mahmud Yunus Batusangkar)
PERKEMBANGAN hukum pidana di Indonesia kini bergerak semakin kompleks seiring laju globalisasi, teknologi, dan ekonomi. Dunia sosial yang berubah cepat melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak lagi dilakukan oleh individu semata, melainkan juga oleh entitas korporasi. Salah satu kasus paling mencolok adalah korupsi yang dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi sistem hukum nasional karena menyentuh ranah ekonomi, politik, dan moral masyarakat sekaligus. Dari sinilah muncul pertanyaan penting: bagaimana negara harus merumuskan perbuatan materil (actus reus) korporasi agar pertanggungjawaban pidananya adil dan rasional?
Masalah ini tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan hukum positif yang kaku dan diperlukan pendekatan filosofis melibatkan tiga aspek ontologi, untuk memahami hakikat korporasi sebagai pelaku hukum; epistemologi, tentang bagaimana mengetahui dan membuktikan kesalahan korporasi; serta aksiologi, mengenai nilai moral dan tujuan sosial penegakan hukum. Dengan kata lain, pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi bukan semata soal pasal dan ayat, tapi juga soal bagaimana ilmu hukum berperan dalam kehidupan nyata: apakah sebagai ilmu murni, ilmu dasar, atau ilmu terapan.
Pada tataran keilmuan hukum memiliki posisi unik, hukum tidak seperti fisika atau biologi yang bersifat objektif dan bebas nilai. Scholten (Paul Scholten, 2003) menjelaskan hukum selalu berurusan dengan manusia dan nilai kemanusiaan yang bersifat normatif dan preskriptif. Artinya hukum tidak hanya menjelaskan das sein tetapi juga menentukan das sollen. Sehingga hukum termasuk dalam ilmu dasar yang berfungsi mengembangkan teori dan asas untuk membimbing praktik. Namun hukum juga harus tampil sebagai ilmu terapan ketika asas dan teori itu diimplementasikan dalam bentuk kebijakan publik, undang-undang, atau putusan pengadilan.
Kedudukan ganda inilah yang membuat hukum selalu berada di antara teori dan praktik. Sebagai ilmu dasar hukum melahirkan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana. Tetapi sebagai ilmu terapan, hukum harus menjawab persoalan empiris seperti bagaimana asas-asas itu diterapkan ketika korporasi melakukan korupsi. Maka perumusan perbuatan materil korporasi menjadi ruang pertemuan antara nilai ideal dan realitas sosial.
Filsafat ilmu melalui Pure Theory of Law (Kelsen, 2011) memandang hukum sebagai sistem norma yang otonom, bebas dari politik dan moral serta menginginkan hukum yang murni dan netral. Namun pendekatan ini dinilai terlalu formalistic, realitas sosial hukum tidak bisa steril dari nilai moral karena fungsinya bukan hanya menjaga kepastian untuk mengatur manusia (Annurriyyah et al., 2024) tetapi juga menegakkan keadilan (John Rawls, 2019). Bahkan keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem hukum dan jika hukum hanya mengejar kepastian tanpa keadilan, pada akhirnya kehilangan legitimasi moralnya (Joseph Raz, 1979).
Lalu kapan muncul terobosan dari ilmu murni (Hans Kelsen, 2008) ke ilmu dasar dan terapan? Kuhn (Thomas S. Kuhn, 2020) menjelaskan bahwa setiap ilmu akan mengalami krisis paradigma ketika teori lama tidak lagi mampu menjawab realitas baru. Hukum pidana, krisis itu terjadi ketika teori klasik pertanggungjawaban pidana yang berfokus pada individu tidak bisa menjangkau kejahatan korporasi. Korporasi sebagai badan hukum bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara, tapi secara tradisional dianggap tidak bisa dipidana karena tidak memiliki kesadaran moral (mens rea).
Krisis ini memicu inovasi dalam teori hukum, melahirkan konsep baru seperti Identification Theory, Vicarious Liability, dan Strict Liability (Nani Mulyati, 2018). Ketiganya menandai pergeseran cara pandang bahwa korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, baik melalui tindakan direksi, karyawan, maupun kebijakan internal perusahaan. Namun, dalam praktik di Indonesia, masih sering terjadi ketegangan antara das sollen dan das sein (Ismansyah, 2015). Secara ideal hukum pidana harus menegakkan keadilan substantif, termasuk korporasi pelaku korupsi. Realitanya hukum sering tunduk pada kepentingan ekonomi dan politik, misalnya Pasal 4B UU BUMN memberi perlindungan bagi direksi yang bertindak dengan itikad baik meski merugikan negara. Ketentuan ini berbenturan dengan doktrin strict liability dalam UU Tipikor yang menegaskan bahwa pembuktian niat jahat tidak diperlukan untuk menjerat pelaku korupsi.
Pertentangan tersebut menunjukkan adanya legal gap idealisme hukum dan praktiknya (Achmad Ali, 2015) fenomena ini sebagai bentuk jurang epistemik, di mana hukum kehilangan daya moral karena terjebak kepentingan pragmatis. Akibatnya korporasi sering lolos dari jerat hukum, ketimpangan ini menandakan adanya legal gap dalam kebijakan pertanggungjawaban korporasi pada tipikor.
Dari sudut pandang filsafat ilmu kebijakan formulasi hukum pidana terhadap korporasi harus memperhatikan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat korporasi sebagai subjek hukum; epistemologi menyangkut cara memperoleh dan membuktikan pengetahuan hukum tentang kesalahan korporasi; sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Hukum yang ideal harus menyeimbangkan ketiganya tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga menjamin keadilan dan kemanfaatan publik.
Reformasi hukum pidana korporasi seharusnya berfokus pada penyelarasan antara teori dan kenyataan sosial. Hukum tidak cukup hanya patuh pada teks undang-undang, tetapi juga harus berpihak pada keadilan. Dalam konteks korupsi korporasi, hal ini berarti memastikan agar hukum mampu menjerat pelaku yang bersembunyi di balik entitas perusahaan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam manajemen.
Pada akhirnya pembaruan kebijakan formulasi perbuatan materil korporasi adalah perjalanan panjang ilmu hukum dari teori menuju praktik, dari norma menuju realitas. Seperti diingatkan Paul Scholten, hukum yang berhenti pada teks akan mati bersama teksnya sedangkan hukum yang hidup bersama masyarakat akan tumbuh bersama keadilan. Karena itu hukum harus menjadi jembatan antara idealisme dan kenyataan, antara ilmu dasar dan ilmu terapan, agar tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga benar secara moral dan adil secara sosial.(**)